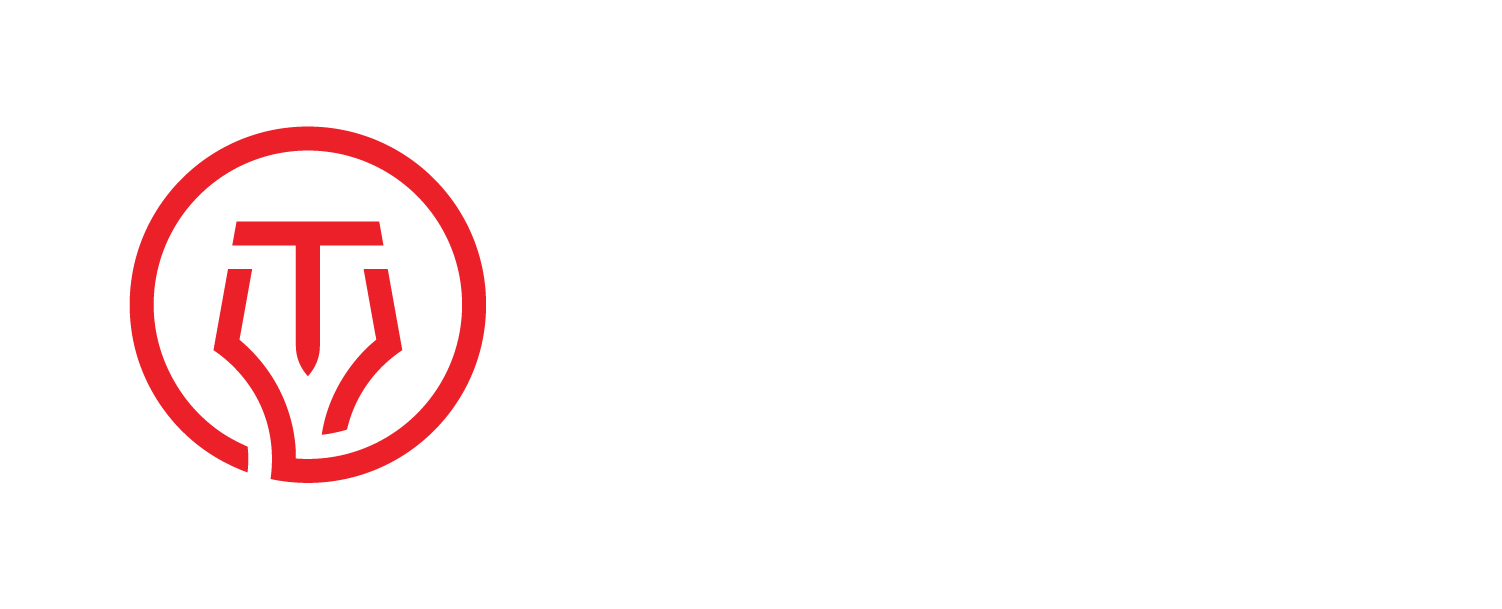Kolom
Wednesday, 06 June 2018 23:35 WIB
Siapa Berani, Siapa Diam
Author pwtsetiadi
Oleh Purwanto Setiadi
Perubahan dalam masyarakat terkadang hanya memerlukan satu tindakan sederhana: ada orang yang mau secara terbuka menentang perilaku tak beradab, diskriminatif, dan bahkan amoral yang sedang merajalela, atau mengintervensi untuk meluruskan yang bengkok-bengkok itu.
Dalam kenyataannya, sering orang-orang semacam itu justru langka. Karenanya, muncul pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang menjadikan seseorang mau menentang arus–yakni diamnya sebagian besar orang menghadapi kesewenang-wenangan, penindasan, fitnah. Dengan perkataan lain, pertanyaan ini mempersoalkan kualitas pribadi seperti apa yang bisa mendorong seseorang berani bersuara, menghardik penyimpangan dari standar kepatutan, norma, yang diakui umum.
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terasa penting saat ini. Jawabannya sangat boleh jadi bakal ikut menentukan apakah, sebagai bangsa, kita akan sanggup melanjutkan langkah maju, mewujudkan cita-cita masyarakat beradab, yang madani, atau hanya berjalan berputar-putar di tempat–jika bukan malah terantuk rintangan dan jatuh berdebam-debam (dan bubar).
Sudah sangat gamblang betapa kita, perlahan-lahan sejak pemilu 2014, menghadapi kelompok kecil muslim yang justru bersuara lantang, memaksakan kebenaran tafsirnya yang terkadang ekstrem atas ajaran Islam, terus mendominasi opini tentang mana yang saleh dan mana yang mursal (bahkan murtad), serta memecah belah sesama umat dan antarpenganut agama yang berbeda-beda. Pendapat mereka tak selalu benar, malah kerap semata-mata merupakan pemutarbalikan dari teks Al-Quran dan tradisi yang dijalankan Nabi Muhammad, serta “gorengan” atas fakta-fakta yang nihil. Masalahnya tak sedikit yang mendengarkan mereka, termasuk kalangan yang berharap bisa mengambil keuntungan politik, sehingga keberadaan mereka jadi sulit diabaikan.
Bukan tak ada yang mencoba mematahkan aneka klaim dan membendung fitnah tak berkesudahan itu. Masalahnya tindakan ini seakan-akan mirip teriakan di tengah badai, tiada gaungnya. Sangat boleh jadi hal ini tak terelakkan karena, pada umumnya, upayanya datang dari tataran yang kelewat tinggi–walau sebetulnya otoritatif–dan terkesan berpencaran, tak solid serta tak frontal. Di tingkat bawah, juga yang bersifat “lokal”, yaitu di lingkungan kecil perumahan, pertemanan, dan komunitas, hampir setiap orang seperti sakit gigi.
Hampir, berarti ada. Jumlahnya saja yang tak banyak. Impaknya pasti sangat minimal, kalau bukan nihil sama sekali. Tapi dari yang sedikit, yang berani menghadapi bully dan konfrontasi, itulah sebetulnya bisa diidentifikasi faktor-faktor penentunya yang bersifat internal. Pengetahuan mengenai faktor-faktor ini, yaitu berupa karakteristik kepribadian, berpeluang membantu mencari cara untuk mendorong semakin banyak orang berhenti bungkam saja menghadapi suasana yang kibang-kibut.
Untuk mengidentifikasi profil orang yang berani bersuara itulah Alexandrina Moisuc, psikolog dari University of Clermont Auvergne (Prancis), dan koleganya belum lama ini melakukan penelitian yang melibatkan 1.100 sukarelawan dari Austria hingga Prancis. Temuan mereka, yang diterbitkan di British Journal of Social Psychology pada Februari lalu, menepis dugaan bahwa para pemberani itu berprofil sebagai bitter complainer–orang yang melancarkan permusuhan kepada orang lain untuk mendongkrak gengsinya yang rendah. Sebaliknya, faktor-faktor di balik perlawanan terhadap ketidakadilan sosial justru berupa kepercayaan diri, tekad yang kukuh, kematangan dalam mengendalikan emosi, keinginan membantu orang lain, dan perasaan nyaman dalam menyatakan pendapat. Orang dengan karakteristik semacam ini masuk ke dalam kelompok well-adjusted leader.
Penelitian itu dijalankan dengan cara menempatkan para sukarelawan ke dalam serangkaian skenario hipotetis–kepada mereka diputarkan video klip atau diberikan teks yang bisa dibaca. Skenario-skenario ini menghadapkan para sukarelawan dengan beraneka perilaku antisosial seperti orang sedang merobek poster di tempat umum, meludah di trotoar, menendang-nendang kaleng bir tapi lalu membiarkannya tergeletak begitu saja di jalanan, atau melemparkan baterai bekas ke dalam pot bunga di taman publik. Respons para sukarelawan beragam, dari yang sama sekali bungkam, menghela napas, hingga menegur pelaku, secara sopan maupun kasar.
Para sukarelawan juga diminta menilai seberapa marah mereka, dari sudut pandang moral, terhadap insiden-insiden yang dihadapkan kepada mereka. Perasaan paling kuat berkaitan erat dengan keinginan yang juga kuat untuk bertindak. Selain itu, para sukarelawan diminta mengevaluasi diri sendiri, menilai karakteristik personal mereka.
Memang ada kelemahan dari penelitian itu. Misalnya fakta bahwa para sukarelawan hanya diminta menilai karakater personalnya, yang dalam kenyataannya bisa tak pasti. Secara khusus, dalam hal ini, reaksi orang bisa saja berbeda bila berada dalam situasi nyata. Tapi temuan Moisuc dan kawan-kawan konsisten dengan temuan-temuan terdahulu. Dan, bagaimanapun, temuan itu bisa memberikan gambaran mengenai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk terus mempromosikan kehidupan bermasyarakat yang beradab.
Tentu saja, wajar bila ada pertanyaan mengganggu yang tak bisa dinafikan ini: setiap orang umumnya ingin menjadi pahlawan dalam kehidupannya, sekurang-kurangnya menjadi orang baik yang berguna bagi lingkungannya, tapi mengapa hanya sedikit yang benar-benar mau bertindak ketika situasi memang menuntut untuk itu?
Penulis adalah wartawan, penyunting buku Jurnalistik Dasar: Resep dari Dapur Tempo, pernah menjadi Redaktur Pelaksana Tempo. Ia juga menulis tentang musik, kopi, dan sepeda di akun Facebook-nya.
Baca juga : Badan Siber dan Sandi Negara Akan Gandeng BIN, TNI, Polri